Sudah saatnya para ulama, khususnya yang selama ini aktif, atau minimal simpatisan parpol tertentu, untuk mengundurkan diri. Dan, seyogyanya segera kembali ke pesantren, ke masjid, ke mushalla, atau ke surau. Inilah yang lebih berkah; insya Allah.
Keterlibatan beberapa oknum ulama di berbagai parpol. Sungguh telah membawa kenyataan yang memprihatinkan. Bukannya dakwah Islam, pendidikan Islam, dan jihad Islam semakin baik dan bermanfaat buat bangsa Indonesia
Akibatnya agama sekadar dijadikan alat untuk memupuk populeritas, meraih kekuasaan, berkomplot dengan kaum politisi, dan yang jelas, semakin jauh dengan umat. Bisa dilihat sekarang ini kondisi umat Islam, seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka sesuka hatinya "menerjemahkan" agama. Dikarenakan, mereka meniru langsung praktek dari kaum ulama, yang sementara ini banyak membuat umat bingung; bahkan di sebagian kelompok masyarakat sudah banyak yang sinis dengan peran ulama.
Sekaranglah, peta sosial keulamaan dibuat oleh Allah azza wa jalla. Siapa yang benar-benar ulama-Nya. Dan, siapa-siapa yang ulama cinta jabatan, cinta dunia, dan pengikut hawa nafsu. Betapa sangat memalukan perbuatan mereka. Di mana tidak?!
Fatwa agama dibuat main-main. Lebih celaka lagi, banyak dari mereka telah berani menjadikan riswah sebagai sarana "mendulang" rupiah. Meski dengan alasan kelembagaan yang menerima "sumbangan". Sangat mengerikan apabila keilmuan yang dimiliki, justru difungsikan untuk membenarkan perbuatan tercela. Tidakkah riswah itu sangat tercela?!
Sangat lucu, apabila ada seorang ulama, begitu berharap untuk menjadi anggota dewan. Yang lebih lucu lagi, bila seorang ulama berharap menjadi pejabat. Tidakkah seharusnya mereka tahu, bahwa dalam matrik sosial; kaum ulama itu semestinya memerintah kaum umara`, demikian menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas r.hu. Dan, umara` sudah semestinya memerintah masyarakat. Jadi, seorang ulama adalah begawan yang tidak harus menjadi raja. Sebab, seorang begawan itu telah menjadi tumpuan curhat dari umat dan umara`.
Sekarang apa yang terjadi? Tahun lalu, sekelompok ulama, yang kebetulan ditakdirkan Allah memiliki pondok pesantren. Mengeluarkan fatwa, bahwa memilih pemimpin perempuan hukumnya haram. Namun selang beberapa tahun, dengan enaknya fatwa itu dirubah, memilih pemimpin perempuan menjadi boleh dengan alasan yang dicari-cari. Ternyata sederhana, "Haram bagi lawan politik kaum ulama. Dan, boleh karena konco politiknya."
Semestinya, seorang ulama harus arif dan bijaksana. Semua yang dikeluarkan atas fatwa atau pendapat pribadinya sekali pun, harus berdasarkan ilmu pengetahuan diniah. Bukan hawa nafsu. Atau, like and dislike. Akibatnya, maka antara satu ulama dengan ulama yang lain tak jarang telah terjadi benturan kepentingan. Yang seringkali diikuti dengan benturan sosial di wilayah shantri-nya.
Marilah kita berpikir jernih. Jika memang tidak siap jadi ulama-nya Allah. Ya pilih saja aktifitas kehidupan yang lain. Toh untuk memperjuangkan agama Allah tidak selalu harus menjadi ulama. Ketimbang menjadi ulama. Tapi harus mengajukan proposal ke sana
Tidak dilarang seorang ulama berpolitik. Yaitu, berpolitik kebangsaan. Dan, harus jelas berani meninggalkan politik praktis. Jika kita mau jujur, dalam 24 jam kehidupan seorang ulama, insya Allah tidak ada kesempatan untuk berpikir yang neko-neko. Sebab, untuk meng-istiqamah-i dan men-dawam-kan nilai-nilai keulamaan saja sudah menyita waktu.
Yang alfaqir khawatirkan, jangan-jangan berbaju ulama. Tapi sebenarnya, mereka adalah musang berbulu ayam. Dan, masyarakat kita memang latah memberikan julukan untuk para ulama, dengan sebutan seperti: kiai, ustadz, gus, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan. Yang apabila hatinya lalai akan menjadi sarana "pendulang" kemudahan fasilitas dan kenikmatan duniawi dari akibat mendapat julukan-julukan tersebut; na'udzu billâhi min dzâlik.
Seorang ulama yang ikut main politik praktis. Sama halnya dengan harimau masuk kebun binatang. Padahal kita tahu, bahwa tempat alami seekor harimau adalah di hutan belantara. Begitu juga dengan kaum ulama. Di negeri ini tempat ulama adalah pesantren, masjid, mushalla, surau, dan yang sejenisnya. Karenanya, para "harimau" harus hati-hati jangan sampai terkena "jebakan" kaum pemburu yang seringkali berganti-ganti baju, guna mengelabuhi buruannya.
Alfaqir sangat menekankan, seorang ulama wajib memahami politik kebangsaan. Bahkan, sudah saatnya sekarang ini seorang ulama menguasai juga politik global. Ini tuntutan jaman, guna meningkatkan pelayanan terhadap umat. Saatnya seorang ulama menguasai teknologi internet, dan piranti percepatan informasi yang lainnya. Sebab, dari sini seorang ulama akan terlibat secara aktif dalam jaringan masyarakat global. Harus disadari, bahwa bangsa ini dan masyarakat Indonesia


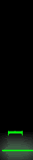



 majalahmayara@yahoo.co.id
majalahmayara@yahoo.co.id  the_maqway99@yahoo.com
the_maqway99@yahoo.com pangeran_halilintar@yahoo.com
pangeran_halilintar@yahoo.com  pesonamerahputih@yahoo.com
pesonamerahputih@yahoo.com  arifkhunaifi@yahoo.co.id
arifkhunaifi@yahoo.co.id 



0 komentar:
Posting Komentar