*Dimas Indianto S
Senja sebentar lagi sempurna. Keemasan matahari telah menggantung di mataku. Tetapi rintik hujan perlahan menyelinap di antara bayangan senyummu di pelupukku. Semakin lama ku pandangi warnamu, hujan semakin deras. Namun, seperti apapun cuacanya, kau selalu datang tepat waktu. Kini, kubayangkan kau sedang duduk gelisah di halte itu--tempat pertama kau dan aku bertemu dalam hujan, saat itu kau kerepotan membawa barang belanjaan, kau panik dengan hujan yang membasahi rambutmu, dan ketika itu aku menyodorkan payung, lalu kau dan aku berdua menundukkan hujan. Dan kau ku antar ke dalam halte yang di situ banyak orang mendekap sunyi dengan jaket mereka, sampai sebuah mobil mewah menyeretmu dari hadapanku--, seorang diri. Menatap layar HP yang sinyalnya nyala-mati, sembari menggosok-gosokkan lenganmu dengan telapak tanganmu yang mengisut untuk mengusir dingin yang menggerogoti kesabaranmu yang makin entah. Sudah satu jam lebih dari waktu yang kau aku sepakati. Dan aku masih meringkuk di kamarku. Sudah beberapa kali kau menelepon, tapi selalu putus. Sinyalnya pasti terganggu oleh cuaca yang payah.
Dari balik jendela kamarku, aku hanya membeku, menatap hujan yang bermain-main dengan angin. Jalan-jalan penuh dengan genangan. Rerumputan tak lagi bisa bergoyang. Tubuhnya enyah terendam dingin yang panjang. Jendela kaca di wajahku perlahan buram, berembun. Ku lentikkan jemariku untuk menyekanya, dan wajahmu yang gelisah seperti tersketsa di sana
Tersebab itu harus aku katakan, “Maaf, senja ini aku tak bisa menepati janji--untuk menyudahi rindumu yang berapi-api---. Aku yakin kau maklum. Senja ini tak seperti biasanya, terang seperti fotomu yang kuselipkan di pelupukku. Langit begitu gelap, tak mungkin aku menerobosnya. Sedang di sini aku menemani nenekku yang tengah berbaring menahan sakitnya. Adik-adikku belum pulang dari pasar—mencari kertas-kertas bekas untuk kemudian dijual, sekedar menambah uang jajan mereka--. Jika aku pergi nenek akan sendirian.
***
Halte sepi. Biasanya setiap sore banyak orang lalu lalang berpulang dari bermacam kesibukan. Kursi panjang yang terbuat dari kayu berwarna hijau tua--yang dulu kau aku duduk bersama, setelah kau menawari payung untukku, sebab aku kerepotan dengan belanjaanku dan bajuku terkena basah. Dan kau mengajakku bercerita kemari-kesana, menghilangkan dingin dengan senyummu yang ramah—tampak basah oleh embun hujan. Aku duduk menggigil di ujung bangku, sendiri. Tapi kau tak juga datang. Bagaimana pun cuacanya, kau memang jarang tepat waktu tapi itulah uniknya dirimu, yang membuatku berat melupakanmu. Ah entahlah!
Hujan masih nericis lirih. Beberapa kali aku dekap-dekap tubuhku, ku usap-usapkan telapak tanganku, sesekali ku gosok-gosokkan pada lenganku secara silang. Aku memang mulai merasa gelisah. Gelisah yang indah. Sudah satu jam lebih aku menantimu. Dan batang hidungmu belum juga muncul.
Hujan makin mengencangkan arusnya, barangkali di tempatmu pun sama. Mungkin sebab itu kau belum juga datang atau bahkan tidak bisa datang. Beberapa kali ku kirim sms, tak terkirim juga. Beberapa kali ku telpon, tak terhubung juga. Hujan begini, pasti sinyalnya buruk. Tapi tak apa. Aku akan menunggumu hingga senja ini terang. Pun jika kau tak bisa datang juga tidak masalah. Apalagi aku tahu beberapa hari lalu nenekmu baru pulang dari rumah sakit. Dan tentu sebagai cucu yang baik sekaligus paling tua, kau memang seharusnya menemani nenekmu istirahat, menghibur dan mengingatkan jika sudah waktunya minum obat. Salahku juga, memintamu bertemu pada musim hujan seperti ini. Ini benar-benar bukan masalah. tak apa. Aku hanya merindukanmu. Sudah sekitar dua minggu kita tidak bertemu. Dan sepanjang ini membuat rinduku berapi-api, adakah kau juga merasakannya?
***
Benarlah bahwa cukup lama jeda kita tak berjumpa. Perjumpaan terakhir adalah saat aku menemani nenek dirawat di rumah sakit. Selepas menjenguk nenek dengan separcel buah, kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar, setelah saling terdiam agak lama, dan itu pun dengan suara teramat lirih.
“Sudah berapa hari nenek dirawat?” tanyamu lembut sembari mengelus-elus tangan nenek yang tengah tertidur pulas.
“Dua hari”
“Kata Dokter, apa sakit Nenek?”
“Katanya cuman terlalu lelah”
“Itulah. Pasti nenek terlalu capek. Sudah ku bilang, Nenek suruh banyak istirahat saja di rumah”
Aku hanya terdiam mendengar petuahmu yang penuh perhatian pada keluargaku.
“Maaf, aku tak bisa berlama-lama. Aku harus kembali ke rumah. Kalau keadaan nenek membaik. Tolong kabari aku.”
Aku tersenyum dan berterima-kasih, sebelum kau pergi dan mencium tangan nenek.
Entahlah! hubungan kau dan aku memang tak jelas. Barangkali itu karena perbedaan derajat keluargamu dan keluargaku tak sama. Kau anak dari orang terhormat, kekayaanmu berkelimangan, pendidikanmu hebat. Dan mungkin karena itu pula, terkadang aku merasa, bahwa kau dan aku tak layak untuk bersama.
Dalam dirimu, terbiasa berhidup serba ada, kau ingin ini-itu, keluargamu tak pernah menundanya. Kehormatan keluargamu terdengar di mana-mana, kecantikanmu apalagi, tak perlu ku bertanya. Dan aku sebaliknya: miskin, hidup dalam ambang ketiadaan, keluargaku tak berkecukupan. Itu jugalah kenapa setiap sore adik-adiku bergentanyangan menelusuri gelap pasar mencari sisa-sisa kertas untuk dijual kemudian untuk jajan. Ibu bapakku telah tiada. Dan nenek, sakit tersebab tenaganya habis dikuras untuk bekerja sebagai tukang cuci. Sedang aku, hanyalah seniman miskin, pelukis yang tak tahu arah harus apa ku berkarya. Cukupkah hasil jualan lukisan pun ku tak tahu?! Dan ini, biaya rumah sakit dan berobat nenek aku berhutang kemari-ke sana
***
Hujan belum juga reda. Langit agaknya mulai kedinginan. Berselimutkan awan gelap yang begitu tebal menggantung di atas halte. Jalanan makin tak terlihat, sebab tergenang seperti juga hatiku yang makin tak tenang. Suasana beginilah yang acap membuatku melamunkanmu. Melamunkan hubungan kita yang terus mengalir, lancar, tapi bagai tak bermuara.
Kata cinta kerap kau ucapkan, namun tanganmu masih gemetar untuk melingkarkan cincin di jemariku. Kau mungkin masih menimbang-nimbang tentang keseriusanmu. Padahal usiaku dan usiamu semakin merangkak. Dan lelaki yang melirikku tak terhitung jumlahnya.
Hubungan kita pun masih rahasia. Setahu keluargamu, aku hanya seorang teman perempuanmu yang memberi perhatian lebih pada keluargamu. Jadi keluargamu tak pernah berpikir aneh-aneh tentang kau dan aku. Entahlah, bagaimana kisah ini berujung. Seolah sebuah alamat buruk pula, jika seorang perempuan sepertiku jatuh cinta dengan pemuda dari keluarga sederhana.
Dan keluargaku pun entah. Barangkali tak mau menerimamu tersebab derajat kau dan aku tidaklah sama. Tapi sungguh aku mencintaimu. Bukan harta yang aku ingin, tetapi ketulusan mencinta yang kau punya yang tak pernah ku jumpa pada semua yang ku jumpa.
***
Hujan masih berdebaman. Masihkah kau di sana
Aku pun kemudian berpikir, hal bodoh apa yang telah merasuk ke dalam pikiranku, yang membuatku mencintaimu. Sungguh tak pantas lelaki tak punya, mencintai perempuan keluarga berada. Ini sungguh sebuah kegilaan yang sungguh keterlaluan. Aku tidaklah layak menjadi pendampingmu. Aku hanya pemuda pengangguran. Membahagiakan nenek dan adik-adikku pun ku belum kuasa. Maka, bagaimana mungkin aku mengucapkan ikrar itu padamu. Begini-begini, aku juga tahu apa kewajiban suami pada istri. Karena itulah alasan mengapa aku menunda. Sekali lagi maaf.
***
Makin lama, hujan ini menjadi seperti tangisan. Ngilu dan panjang. Apa mungkin kau datang menemuiku, sedang hujan sederas ini? Ah kau. Selalu aku bertanya begini: bagaimana aku bisa jatuh hati padamu? Jujur, terkadang aku merasa bersalah padamu. Keberadaan keluargaku mungkin membuatmu minder untuk mencintai dan mendekatiku. Tiba-tiba aku memintamu untuk segera mempersuntingku. Meski tidak secara langsung, aku tahu, itu mengganggu pikiranmu.
Apa boleh dikata, ini masalah perasaan. Apa iya, aku harus melepaskanmu. Sedang aku berbeda dengan perempuan lain. Aku tak membutuhkan materi yang lama ini buat kau terganggu, aku sudah punya kemapanan, aku telah bekerja, ayahku punya beberapa perusahaan. Aku tak butuh itu, sungguh! Aku hanya mengidamkan kejujuran, ketulusan dan kesederhanaanmu. Kenyamanan yang mampu kau beri setiap kau berada di dekatku, itulah yang ku inginkan. Dan rasanya, hanya kau seorang dari sekian banyak lelaki, yang mampu memberikan itu. Lalu aku berpikir bahwa mungkin kaulah malaikat yang tuhan kirimkan untuk menemani hidupku. Sepanjang jalan yang kan
***
Hujan ini seolah tak akan berhenti. Entah sampai kapan. Barangkali, sericis inilah perasaanku padamu, hanya saja aku belum bisa melukiskannya, seperti biasanya aku melukis. Apa pun yang terjadi, sepertinya perasaan yang ku pikul ini takkan mungkin goyah. Jadi mana mungkin aku melepaskanmu hanya karena masalah materi. Dalam kamus percintaan, tak pernah mencantumkan materi atau kemapanan sebagai syaratnya. Jadi semua sah-sah saja. Jikalau pun kau benar-benar memaksaku untuk menikahimu sekarang juga, aku akan melakukannya. Tapi aku senang, kau tidak menuntut itu. Kau memang perempuan paling pengertian setelah nenekku. Tapi apa imbalanku?
Sepanjang jalan ini, serasa semua berjalan lancar. Kau dan aku tak pernah menemu masalah dengan keputusan atau yang lain. Setiap kali aku membahas sesuatu kau selalu mencoba menghadirkan saat itu juga. Lagi-lagi, itu sebuah bukti nyata bahwa aku belum pantas untuk menjadi sosok calon suami. Mengapa demikian? Tentu saja. Lelaki yang tak bisa memenuhi kebutuhan perempuannya, ia bukan lelaki. Karena ia lemah. Dan yang kurasakan selama ini, itulah aku. Karena itu sesungguhnya aku perlu sesuatu yang baru untuk menyegarkan hubungan kita yang selama ini baik-baik saja—sebenarnya lebih layak untuk disebut datar-datar saja-- . bagaimana jika aku memberikan kejutan untukmu?
***
Hujan ini sebuah kejutan bagi kemarau panjang. Hei, aku berpikir tentang kejutan. Selama ini, kau tak pernah memberi sebuah kejutan pun untukku. Kado ulang tahun? Itu bukan kejutan yang ku maksud. Entahlah tiba-tiba aku membayangkan jika kau menemui orangtuaku, beserta membawa lukisan wajahku yang kau buat, lalu kau utarakan maksud hatimu, tentang keseriusanmu. Sekali lagi aku tidak mempermasalahkan keberadaan keluargamu. Aku hanya inginkan kau menemaniku, menjadi suami yang sah untukku.
Kau tahu, kenapa selama ini aku selalu penuhi kebutuhanmu? Karena aku tak mau kehilanganmu. Aku mengenalimu sungguh sangat dalam. Aku tahu siapa kau, sosok lelaki yang begitu tangguh menghidupi neneknya dan menyekolahkan adik-adiknya, dan tak pernah mengeluh menjajakkan lukisan-lukisanmu keliling kota
***
Sederas apapun, nanti hujan ini pastilah akan berhenti. Meski seolah tak juga berhenti. Bicara tentang berhenti, aku yakin, aku akan segera berhenti dari citra lelaki tak punya keberanian. Yang selama ini kubangun sendiri. Ya, kenapa tidak? Aku lelaki murni, yang seharusnya memiliki sikap-sikap lelaki murni: tegas, berani, tak mudah putus asa, tidak mengeluh...dan sifat-sifat lelaki yang lain. Benarkah, hanya karena berhadapan dengan perempuan anak orang terhormat lantas aku mejelma lelaki payah? Tidak. Akan kubuktikan padamu.
Ahai, hujan begitu kencang membuat darah lelakiku mengalir lancar. Hujan deras ini membuat pikiran-pikiran yang tersumbat menjadi plong. Menjadi lebih jernih. Baik, baik, setelah hujan yang deras ini. Aku harus menemuimu dalam keadaan yang sudah berbeda, penuh dengan keyakinan yang selama ini kau harapkan ada padaku. Tunggu, tunggu, mengapa harus menunggu hujan berhenti?
“Ah ini hanya hujan!” gumamku, seperti baru tersadar dari sebuah percakapan. Aku berdiri, melangkah ke arah nenek, aku meraih tangannya. Aku mencium dan meminta restunya. Airmatanya menetes dari sela-sela mata kecilnya yang tepiannya mulai mengeriput. Aku menangkapnya sebagai tanda restu untukku. Semoga kau masih menungguku di sana
***
Langit sedah gelap dan hujan masih menyuramkan wajah senja yang kau dan aku begitu suka. Aku menjadi bingung, sebenarnya aku menunggumu tiba atau menunggu hujan reda. Rasanya tak mungkin kau datang. Jadi? Aku menunggu hujan reda? Aih, ini hanya hujan. Mengapa aku tak pulang saja. Ya, sebaiknya aku pulang saja. Tapi, bagaimana kalau nanti kau datang. Karena selama ini kau tak pernah melupakan janji, seberapa pun kau terlambat, kau selalu datang. Aduh, kenapa aku jadi gamang begini?
Saat ini, senja benar tak indah. Hujan turun dengan marah. Kau pun tak mungkin meninggalkan nenekmu yang sedang sakit. Jadi tak mungkin kau datang. Aku pun tak mengizinkanmu datang kalau tahu hujan begini. Ya, ya, sebaiknya kau pulang saja.
“Huft...!” aku berdiri, menghela nafas cukup dalam. Ku ulangi beberapa kali untuk sekedar menenangkanku. Seperti baru saja usai dari perbincangan panjang. Halte sore ini begitu sepi, barangkali karena hujan ini telah merenggut keramaian yang seperti biasanya. Dan aku pun melenggang.
***
Hujan sedikit lebih ramah. Ku kenakan jas hujan alakadarnya. Dengan degup memburu, kukayuh sepeda ontelku—yang selama ini menjadi teman setia menjajakkan lukisanku keliling kota pori sana
Hujan menjadi gerimis, ketika aku mendekati halte itu. Namun, kini, detak jantungku menderas. Aku menggigil, gemetar. Apa karena dingin? Bukan. Tapi lihatlah dari kejauhan aku melihat seseorang tengah terduduk sendirian. “Aku yakin kau pasti setia dan sabar menungguku”. Semakin kuat aku mengayuh sepeda. Tapi!! Setelah ku mendekatinya. Itu bukan kau. Tapi orang lain. Hei, aku tidak percaya ini. Aku bingung. Jantungku mengeraskan detakannya. Aku lumat dalam sekelumit kekecewaan. Apa kau sudah pulang?
“Aku tahu kau akan datang. Jadi aku masih menunggumu di sini.” Tiba-tiba suaramu mendekam di telingaku.
Kau sudah berdiri di belakangku tersenyum. Kau benar-benar seperti sebuah kejutan. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya ingin melafadzkan maaf. Tapi bress, tiba-tiba hujan kembali mendendam. Kau aku berlarian. Kembali ke halte itu. Kau dan aku duduk dan sama-sama terdiam—persis adegan pas kau dan aku pertama bertemu, di halte itu--. Agak lama. Sepertinya tengah sibuk, memilah kata-kata yang ingin kau dan aku ucapkan.
Dan seusai hujan mengurangi derasnya, langit sedikit terbuka. Cuaca terlihat lebih indah. Dan kau, ku antar kerumahmu dengan sepedaku menikmati gerimis di penghujung senja.
*Penulis adalah mahasiswa STAIN Purwokerto


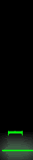



 majalahmayara@yahoo.co.id
majalahmayara@yahoo.co.id  the_maqway99@yahoo.com
the_maqway99@yahoo.com pangeran_halilintar@yahoo.com
pangeran_halilintar@yahoo.com  pesonamerahputih@yahoo.com
pesonamerahputih@yahoo.com  arifkhunaifi@yahoo.co.id
arifkhunaifi@yahoo.co.id 



0 komentar:
Posting Komentar