Kapal-kapal itu selalu muncul dari
balik kabut di tengah laut. Muncul begitu saja laksana kapal hantu. Tidak ada
pertanda isyarat atau lampu. Bahkan derunya begitu lamat membelah riak
gelombang. Ya, kapal-kapal itu muncul begitu saja dari balik kabut. Tak teraba
arah datangnya, tiba-tiba sudah di depan mata para nelayan, menyorongkan
lambungnya yang hitam kokoh. Angkuh betul seolah merekalah empunya lautan,
merintangi jalan atau kadang melaju kencang, seolah hendak menerjang siapa saja
yang berani menghadang haluan. Telah kerap mereka merobek pukat yang
ditebarkan, menabrak bagan, atau bahkan menderu ke arah perahu-perahu sampan,
hingga berlompatanlah para nelayan, menceburkan diri ke dingin air laut
menjelang fajar.
Demikianlah
sejak sekian tahun yang lalu mereka datang. Tidak diundang dan seolah ingin
mengekalkan hukum lama di lautan: siapa yang kuat, ia yang menang! Tak pernah
jelas benar dari mana mereka bertandang (Ya, lantaran telah lama panji dan
bendera memang tak lagi menjadi lambang), dan kian meraja pada tahun-tahun
belakangan.
Tak ada yang mampu memberi mereka
sekadar pelajaran. Karena seperti juga datangnya, mereka pun pergi menghilang
(Tentu, setelah menguras ikan-ikan dengan trawl) tanpa jejak dengan
lamat suara. Seakan lenyap begitu saja ditelan lautan, ke balik kabut tebal
yang mengambang di atas gelombang. Atau, konon karena yang berwenang tak cukup
menggubris keluhan di sepanjang pesisiran, walau telah sekian waktu kapal-kapal
itu menebarkan keresahan (jelas sudah bala bencana!) kepada nelayan.
Hm,
lautan! Siapa yang dapat menyelami misteri
kandungannya? Penuh kemungkinan yang tak terduga, juga perkara! Dan seringkali
mautlah akhir petaruhannya. Maka, dulu ketika A Hauw mengumpulkan segenap
penghuni kampung Pesaren—orang-orang bermata sipit berkulit legam yang
menggantungkan harapan dan masa depan pada asinnya air laut—untuk melawan meski
tahu tipis harapan bakal menang, Paman Cung sebagai kepala dusun hanya menghela
nafas panjang.
“Apa
sudah kalian pikirkan masak-masak semuanya?” air muka lelaki paroh baya itu
sekeruh mendung yang menggantung di atas laut. Tapi wajah-wajah yang berkumpul
telah garang membesi, dengan kesumat dendam tersirat di mata berbaur kecemasan.
Ai, di antara perempuan-perempuan yang
ikut berkumpul di tepi pantai saat itu, Kim Moy—sambil menggandeng tangan anak
laki-lakinya yang baru berumur lima tahun setengah—diam-diam menyusut air mata
yang berlelehan.
***
Telah kukatakan di atas, kapal-kapal
itu selalu muncul begitu saja dari balik kabut tebal. Menderu dalam lamat suara
yang tertelan gemuruh ombak. Kadangkala,
lambungnya yang hitam kokoh tampak berkilau oleh cahaya bulan yang
menyeruak dari balik gumpalan awan. O, di bawah terang purnama yang membuat air
laut berkemilau, kapal-kapal itu laksana raksasa menyeramkan. Begitu mencekam
dan mengancam.
Hingga
tak heran, di kampung Pesaren pun kemudian terlahir dongeng-dongeng seram. Yang
acapkali tercipta lantaran niat baik semata, oleh para orang tua yang ingin
menakut-nakuti anak-anaknya agar tak nakal, bawel dan suka melawan. Apabila
kalian mampir ke kampung kami, masih akan sering mendengar ancaman itu
terlontar dari mulut para ibu: “Jangan main ke laut kalau sudah gelap, Moi! Ada raksasa yang suka makan
anak-anak!” atau “Sudah malam, masuklah ke rumah, Ku! Nanti kau dibawa kapal hantu seperti bapaknya A Kwet!”.
Memang,
sejak sekian tahun silam, puluhan orang telah hilang tak berkabar. Atau kalau
ditemukan sudah membengkak biru di pantai seberang (Syahdan, dikembalikan laut
lantaran baik perangai dalam menjaring ikan, yakin orang-orang), di dekat Pulau
Lampu hingga ke tepian Pulau Dua yang kerap terucapkan dalam sebuah pantun
lama. Bapaknya A Kwet yang suka disebut misalnya, suatu ketika pergi melaut
sebagaimana biasa bersama seorang keponakan, sempat berpesan pamit pada anak
istri namun tak pernah kembali. Lenyap begitu saja ditelan luas lautan,
meninggalkan nama, sedu-sedan anak-istri dan teka-teki, paling tidak kemudian
ancaman yang terlontar pada anak-anak nakal itu.
Anak-anak
yang berkarib dengan nasib tak menentu! Nasib yang digariskan oleh samar garis
pantai dan lautan, laiknya permainan judi kartu Kiu-kiu alias
Sembilan-sembilan. Ya, semenjak kecil mereka seakan telah diharuskan untuk
belajar bertaruh nasib—belajar pula menikmatinya—seperti mereka belajar
bertaruh di atas meja judi.
Di kampung kami, judi memang sudah
menjadi kerutinan, mungkin hampir seperti sarapan. Semangat membanting kartu,
teriakan girang mendapatkan jumlah sembilan atau umpatan kotor atas kartu
buruk, adalah pemandangan dan irama keseharian di tiap sudut kampung. Dan kami,
entah sejak kapan, menafsirnya seirama dengan menebar jaring di lautan.
Ada gairah yang serupa tersimpan. Meja
judi dan lautan, kartu dan jaring, betapa mendebarkannya di dada kami, membakar
darah kami. Nasib untung atau buntung hanyalah petaruhan semata. Tidak lelaki
atau perempuan, tua atau muda.
Bagi kaum lelaki, sehabis pulang
melaut, kartu-kartu dengan segelas kopi kental adalah pelepas penat yang
istimewa, pembalik gairah yang manjur buat menantang lagi ganas lautan. Betapa
nikmat satu ketegangan dibasuh dengan ketegangan yang lain. Untuk yang kurang
beruntung di lautan—yang membawa pulang sedikit tangkapan atau tidak sama
sekali—senantiasa ada harapan tersembunyi di balik kartu-kartu, siapa tahu
nasib yang lebih mujur menanti di atas meja, meski ujung-ujungnya seringkali buntung
lagi! Pun yang membawa pulang berkah lautan, apa salahnya merayakan kemenangan
semalaman dengan bergembira bersama angka-angka, siapa yang bisa menduga kalau
kemujuran datang berganda? Walau kenyataannya lebih kerap ikan-ikan besar dan
segar ludes di atas meja taruhan! Terang dongkol dan sakit hati, tetapi selalu
badan yang penat oleh ombak lautan kembali disegarkan oleh gairah membanting
kartu di atas meja.
Sedang
bagi kaum perempuan, di tepi pantai yang sepi, hiburan apalagi yang dapat
menggantikan rewel anak minta inang dan pengap asap dapur? Sambil bergunjing,
untuk sesaat melupakan rasa cemas menanti suami pulang dari laut, apa salahnya
mempertaruhkan sisa uang belanja?
***
Entahlah, mendung yang menggantung di
langit pada malam suaminya mengumpulkan segenap penghuni kampung Pesaren itu,
di mata Kim Moy terlihat seperti kartu-kartu buruk yang terpentang. Bukankah
sedari kecil ia telah lihai membaca kartu, bahkan mahir menangkap isyarat mujur
atau buntung cukup hanya melihat dua kartu awal?
Tapi
apa dayanya mencegah A Hauw dan para lelaki kampung lainnya yang telah meradang
sekian lama lantaran kapal-kapal asing yang terus bertandang membajak harapan
di balik kartu-kartu itu? Maka sambil menahan isak, ia hanya bisa menarik
tangan anak lelakinya menjauh dari tepi pantai.
Kini
Nen Ku, anak semata wayang itu baru saja berulang tahun ke sembilan (ai, angka
tertinggi dalam judi Kiu-kiu!), tak pernah gentar pada dongeng dan
mengabaikan setiap ujar-ujar mengancam. Setiapkali bocah itu memandang ke laut,
entah kenapa, Kim Moy seolah merasa kedua mata anaknya seperti hendak menantang
gemuruh ombak Laut Cina Selatan (atau para penjarah) yang telah merampas sang
bapak. Penuh kemarahan, persis mata A Hauw suaminya. Dan bila sudah begitu, Kim
Moy sering tergetar, lalu rasa nyeri kembali terasa menusuk dadanya, terkadang
tak mampu ia menahan kesedihan yang berulang meleleh.
Seperti
juga malam ini, Nen Ku tampak berdiri tak bergerak di tepi pantai. Berjaket
usang. Ingin rasanya Kim Moy berlari ke pantai dan menyeretnya pulang, tetapi
kakinya seolah tak kuasa digerakkan. Ia hanya terpaku menatap anaknya dari
kejauhan, dan betapa ia membayangkan yang berdiri di sana adalah A Hauw.
A
Hauw, lelaki yang keras hati itu. Yang bersikukuh melamarnya meski orang tuanya
tak merestui. Kim Moy yakin, tentu bukan perkara mereka bershio sama dan karena
itu konon kurang baik menikah, sebagaimana alasan bapaknya. Tapi Lim Cai, anak
tertua Tauke Lim ternyata
menyukainya dan diam-diam telah menyuruh orang membisiki kedua orang tuanya.
Tentu, di mata orang tuanya, dibandingkan dengan Lim Cai, A Hauw ibarat angka 6
yang tak malu menantang angka 9! Tapi begitulah, kendati berangka rendah,
pas-pasan, A Hauw tak gentar menyorongkan tantangan sebagaimana permainan kartu
Peh alias Poker!
Baginya angka 6 bukan angka terakhir, permainan belumlah selesai. Masih banyak
trik lagi yang belum dikeluarkan, dalam putaran kedua, ketiga, dan seterusnya.
Siapa tahu tiga lembar As atau malah deretan kartu tertinggi menanti, seperti
masa depan yang tak terduga! Kartu, bukankah alangkah serupa dengan laut yang
gelap berahasia? Dan bagi A Hauw adalah amsal hidup itu sendiri.
Tapi
orang tuanya tak juga luluh, apalagi konon Lim Cai telah beriming-iming segala
harta. Mereka pun nekat! Suatu malam bulan mati, ia masih ingat waktu itu
menjelang hari raya Peh Cun1, ia menyerahkan segalanya kepada
A Hauw. Ahai, di tepi pantai Pesaren, di balik sebuah perahu rusak tertambat
dekat sisa pondok warung, mereka bergoyang hingga dini hari!
Ketika
akhirnya ia hamil—tentu, toh apa yang mereka perbuat di malam bulan mati itu
terus saja berulang, orang tuanya marah bukan alang kepalang. Namun mau tak
mau, melepaskannya dengan tak ikhlas kepada A Hauw. Dan tampak merengut begitu
masam tatkala menerima suguhan teh mereka saat Liang Pai2
pernikahan. Ya, apa boleh buat, barang yang sudah bolong terang tak lagi laku
dijual! Tentu saja Lim Cai mundur bergegas sambil mengumpat-mencaci!
Dan
kini, ia mengenang lagi semua itu dengan dada yang semakin sesak melihat anak
lelakinya berdiri termangu di tepi pantai. Sementara di langit, bulan tampak
melengkung bagaikan golok suci Kwan To3. Angin yang berhembus
kencang menghempaskan daun jendela, daun-daun nyiur yang menjulang sepanjang
pantai bergemerisik riuh. Bagaimana pun, sebagai ibu, ia ingin sekali merengkuh
Nen Ku ke balik selimut. Tetapi lagi-lagi langkahnya tertahan oleh butiran air
mata lantaran kata-kata anak lelakinya itu pagi tadi terngiang kembali, tepat
benar menohok ulu hati.
“Umurku
hari ini sudah sembilan tahun, Ma.
Papa dulu bilang, aku boleh ikut melaut, boleh tidur di bagan kalau sudah
sembilan tahun,” gumam Nen Ku yang baru pulang sekolah sambil melahap bubur
ayam buatannya. Kim Moy bagai tersentak, piring yang sedang dicucinya nyaris
saja terlepas dari tangan. Sehingga Dominikus, perantau jauh asal Flores yang
telah lama berdiam di kampung Pesaren itu, yang kebetulan lewat di depan rumah
kaget dan menghentikan langkah. Tiba-tiba saja lelaki hitam keriting itu sudah
ada di depan pintu. Mereka saling bertatapan untuk sesaat.
“Kalau
mau melaut, malam nanti ikut perahu Oom saja! Oom tunggu di tepi pantai!” tukas
lelaki yang masih membujang itu pada Nen Ku lalu bergegas berlalu setelah
mengangguk padanya. Kim Moy tertegun, dan tiba-tiba merasa begitu gelisah.
Entah kenapa! Ia tahu, Domi diam-diam suka meliriknya bila berpapasan dan kerap
gugup kalau bicara berhadapan. Malah beberapa kali dengan malu-malu, lelaki itu
sempat menawarkan diri mengantarnya dengan sepeda motor ketika ia sedang
menunggu bus “Gobu” hendak pergi belanja ke kota kecamatan. Namun selalu ia
tolak dengan halus.
***
Semoga ia bertepat janji! Batin Kim
Moy dalam hati. Atau ia harus segera menyeret Nen Ku pulang, tak tahan lagi
melihat si anak semata wayang sendirian berangin malam menunggu di tepi pantai.
Sudah lewat jam sepuluh, perahu-perahu lain sudah berangkat ke bagan. Kenapa
Domi belum pula muncul? Kim Moy kian gelisah.
Akhirnya
ia melihat lelaki itu juga, muncul dari balik kelebatan semak-semak belukar tepi
pantai dengan lampu stromking
bergoyang-goyang di tangan kanan sementara tangan kirinya menyeret jaring. Nen
Ku tampak berpaling dan segera berlari menyongsong lelaki itu. Dari pintu
rumah, Kim Moy menyaksikan keduanya berjalan beriringan ke laut, lalu berhenti
pada tambatan sebuah perahu. Ia bergegas mencari sandal jepitnya, menyambar
senter yang tergantung di samping pintu, menuruni tangga, dan berlari ke
pantai.
“Kenapa
Mama menyusul kemari?” tanya anaknya ketika ia sampai di pinggir pantai dengan
nafas ngos-ngosan. Ia mengatur nafas dan bertabrakan mata dengan Dominikus.
Lelaki itu tersenyum.
“Hati-hati
di laut Nak, jangan omong jorok sembarangan, nurut sama Oom Domi ya?” Tak
tahan, direngkuhnya tubuh Nen Ku dan diciuminya ubun-ubun anak lelakinya.
Seharusnya ia melarang Nen Ku pergi. Tapi sekali lagi, ia tahu, sebagaimana A
Hauw, anak lelakinya itu nyata mewarisi sifat keras hati dan keras kepala sang
bapak. Susah untuk dibantah apabila sudah punya kehendak! Akhirnya ia berpaling
pada Domi dengan ragu, “Saya titip anak saya, Bang.”
“Tenang
saja Ce, saya tidak terlampau jauh ke tengah,” lelaki itu tersenyum
lebar, mencoba meyakinkannya. Ia segera mengerti, kalau lelaki itu tak melaut
benar malam ini selain sekadar menemani anaknya.
Ia
hanya melambai ketika perahu sampan itu melaju membelah ombak dengan deru motor
yang bising, membawa serta anaknya. Tapi lagi-lagi, tetap saja ia tak bisa
menahan air mata. Seiring perahu motor yang kian menjauh, ia seolah melihat
lagi pemandangan pada malam yang mendung itu. Ketika semua lelaki kampung
berarak ke kelenteng Kwan Ti di tengah kampung dipimpin suaminya. Semuanya
dengan takzim membakar hio di depan altar sang dewa, mengucapkan doa memohon
perlindungan sebelum akhirnya membawa kertas-kertas phu4 ke
tepi pantai, membakar dan melarungkan abu kertas-kertas berisi mantera dewata
itu ke laut.
Tapi
A Hauw tak pernah kembali. Hanya kemejanya yang basah oleh air laut bercampur
darah!
Ia
menggigit bibir menahan suara tangis ketika perahu sampan yang membawa anaknya
tinggal setitik kerlip dalam gelap di antara kabut yang mulai turun di
kejauhan. Di langit, tampak olehnya bulan sabit masih tergantung muram.
Menyerupai golok suci Kwan To milik Dewa Kwan Ti, sang dewa perang… Dan
mendadak ia menggigil membayangkan kapal-kapal itu bermunculan lagi dari balik
kabut tebal yang mengambang. Entah kenapa, dalam benaknya terpentang pula
kartu-kartu yang berjumlah buntung di atas meja petaruhan!(*)
Catatan
- Pesta Laut
setiap tanggal 5 bulan Go Gwee Imlek, masih rutin digelar oleh
masyarakat Tionghoa di Pulau Bangka.
- Menghantarkan
teh kepada orang tua dalam adat pernikahan Cina.
- Golok lengkung
bercula yang bertangkai panjang milik Dewa Kwan Ti (baca epos SAM
KOK—The Three Kingdom).
- Kertas kuning
persegi panjang yang ditulisi mantera sebagai jimat/ penangkal bala.
¨ Sunlie Thomas Alexander, mahasiswi Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas
Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Menulis cerpen, puisi, esai, dan
catatan sepakbola di berbagai media, baik cetak maupun
online. Buku cerpennya yang telah terbit berjudul
Malam Buta Yin (Gama Media, 2009). Saat
ini sedang menyiapkan penerbitan dua buah bukunya yang lain,
Istri Muda Dewa Dapur (kumpulan cerpen)
dan
Sisik Ular Tangga (kumpulan
puisi). Ia aktif di Parikesit Institute, Yogyakarta dan mengelola sebuah
penerbit indie, Ladang Pustaka.
Email: ladangbiru2@gmail.com
No. Kontak: 0852-6732-8612







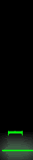



 majalahmayara@yahoo.co.id
majalahmayara@yahoo.co.id  the_maqway99@yahoo.com
the_maqway99@yahoo.com pangeran_halilintar@yahoo.com
pangeran_halilintar@yahoo.com  pesonamerahputih@yahoo.com
pesonamerahputih@yahoo.com  arifkhunaifi@yahoo.co.id
arifkhunaifi@yahoo.co.id 


